Oleh: Faizunal A. Abdillah, Pemerhati sosial dan lingkungan – Warga LDII tinggal di Serpong, Tangerang Selatan.
Sampai usia setengah abad, masih saja diri ini dikebiri dengan yang namanya logika. Entah darimana asal-muasalnya. Bisa jadi karena pernah dididik lama di bangku sekolahan. Semua-semua harus bisa diterangkan dengan kata-kata. Harus ada hitung-hitungan di atas data dan fakta. Ditambah asumsi-asumsi. Tidak melulu urusan baik, ketika berurusan yang jelek pun sama. Dan harus masuk di dalam lingkar kepala. Bisa dicerna dan mengalir mengikuti selera dan teori. Bahkan sampai butuh bertahun-tahun pun tak mengapa. Asal terpuaskan dengan mendapatkan sebuah jawaban. Akhirnya sampai mendarah-daging, masuk ke dalam lubuk hati, dan jadi mimpi; Ini yang saya cari!.
Ketika rambut mulai memutih, yang harusnya pikiran semakin jernih, tetap saja nestapa. Belum bebas, apalagi merdeka. Hanya slogan saja, sudah meninggalkan “dunia hitam”. Nyatanya, masih banyak dicandu debu-debu sesat sebab-akibat. Belum mengerti hakikat kehidupan yang seharusnya, sudah jumawa. Apalagi jika mengerti yang sebenarnya. Bisa jadi gila. Setiap nikmat dimaknai sebab, dan setiap musibah diartikan akibat. Berputar tanpa ujung dan pangkal. Mungkin pengaruh zaman. Bisa juga oleh lingkungan sekitar. Atau karena salah pengelolaan dan gagal paham. Lalu, dimanakah letak keimanan?.
Maka, ketika menyimak kisah Nabi Ibrahim, barulah merasa kebodohan-kebodohan yang telah lama melanda. Kalau boleh minta penjelasan, pasti Nabi Ibrahim dulu akan melakukannya; kenapa seorang bapak harus menyembelih anaknya. Tapi itu, tidak dilakukan. Karena ia tahu, keimanan tak butuh penjelasan. Jawabannya datang kemudian setelah melewati bukit dan lembah serta prosesi penyembelihan. Bahwa itu adalah sebagai ujian ketaqwaan. Buahnya, Allah mengganti dengan gibas Habil yang gemuk dari surga. Simaklah dengan detail, pesan Allah berikut:
“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, “Hai Anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab, “Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia, “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, “Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS Ash-Shoffat:102-107).
Maka, ketika menyimak kisah Nabi Ayub, baru merasa kedangkalan-kedangkalan itu muncul ke muka. Menyeruak. Banyak orang berpikir kalau kena musibah itu akibat ini dan itu. Kalau boleh minta penjelasan, pasti Nabi Ayub akan melakukannya; kenapa ia harus menderita kudis 18 tahun, ditinggal istri dan semua anak-anaknya. Tapi itu tidak dilakukannya. Keimanannya telah memutus paradigma sebab-akibat dengan mengatakan bahwa ia malu, jika menuntut kepada Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadanya selama ini lebih banyak dibanding sedikit musibah yang tengah diterimanya. Ia tidak butuh penjelasan. Keimanan menuntunnya mengingat kenikmatan yang banyak, daripada mengeluhkan cobaan yang sejenak. Semua terangkum indah dalam Kitabnya;
“Dan ingatlah hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Rabb-nya: “Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.” (Allah berfirman): “Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.” Dan Kami anugerahi dia (mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).” (QS. Shaad: 41-44).
Maka, ketika membaca ulang kisah Rasulullah ﷺ yang bengkak dan pecah kakinya karena ingin menjadi hamba yang bersyukur, baru merasa bahwa diri ini dungu sebenar-benarnya. Predikat iman yang kita sandang kadang beraksi berlebih. Over acting. Terhadap hal-hal yang harusnya kita terima saja, justru malah kita bernafsu meminta penjelasan. Sebaliknya, terhadap hal-hal yang perlu dipersungguh dan diagungkan justru kita terbuai dan mengabaikannya. Dan pada saatnya seharusnya bertanya, justru diam merasa sudah faham. Kadang malah mengatakan; gak boleh bertanya. Astaghfirullah! Dan akan semakin dalam lagi, jika menyitir hadits berikut ini. Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:
دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Malu rasanya, ketika mengaku iman, tapi masih menonjolkan logika. Malu rasanya, ketika mengaku iman, tapi masih terkotak-kotak dengan sebab-akibat. Padahal seharusnya mudah, hanya sami’na wa atho’na mastatho’na (kami mendengar, taat dan mengerjakan sak pol kemampuan). Malu rasanya, mengaku iman, tapi tidak getol dalam ibadahnya. Sebab apapun yang kita jalani dan hadapi, harusnya hanya satu penjelasannya, yaitu karena keimanan. Lain tidak.









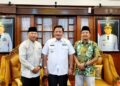



ajkk perkelingnya.
Nasehatnya bikin nyaman, adem dihati…
Alhamdulillaahi jazakallaahu khoiro, menyentuh 🙂